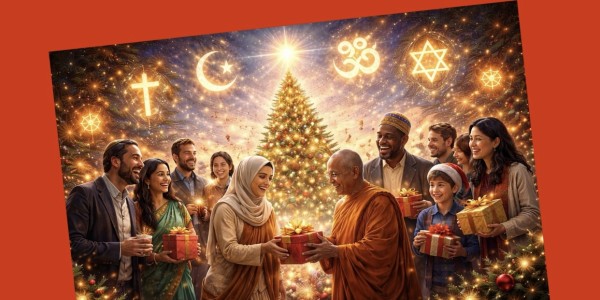Telusur.co.id -Penulis: Qanita Ayu Prayogo, mahasiswa Ilmu Administrasi Fiskal, Universitas Indonesia.
Plastik merupakan bahan yang dipakai kehidupan sehari-hari. Namun penggunaan plastik dapat menimbulkan masalah dalam kehidupan bumi. Menurut riset Jambeck (2015), Indonesia menempati urutan kedua sebagai negara penghasil sampah plastik terbesar kedua di dunia. Selain itu, menurut data Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan (KLHK) (2020) total sampah Indonesia memiliki rata-rata 185 ribu ton per hari.Potensi kerusakan yang disebabkan oleh sampah plastik yang hanya menumpuk di tempat pembuangan sampah tidak hanya mempengaruhi penampilan kota namun sampah plastik yang bercampur dengan tanah mempengaruhi tanaman dalam mengasimilasi nutrisi dan mengurangi produktivitas pertanian (Zhu, 2011). Selain itu sampah plastik yang tidak dikelola dengan baik merusak ekosistem laut dan membahayakan lingkungan alam. Catatan Badan Pusat Statistik menunjukan 72% masyarakat Indonesia tidak peduli terhadap sampah plastik dan memiliki kesulitan dalam pemilahan sampah.
Dalam kaitan ini, kebijakan cukai terhadap produk merupakan salah satu metode bagaimana mengendalikan konsumsi dan sampah plastik. Pada tahun 2016 Kementerian Keuangan mengusulkan kepada DPR untuk mengendalikan konsumsi plastik melalui cukai. Selain itu Februari 2019, DPR Komisi XI menyetujui penetapan Barang kena Cukai Plastik. Menurut Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan (DJBC), Iyan Rubiyanto (2024) bahwa empat jenis produk direncanakan dalam cukai produk plastik yaitu kantong plastik, kemasan plastik multilayer, styrofoam, dan sedotan plastik.
Cukai Plastik ditujukan untuk mengendalikan konsumsi masyarakat Indonesia dengan berbagai eksternalitas negatif yang dihasilkan dari produk plastik bagi lingkungan dan kesehatan. Pengenaan cukai atas plastik membuat adanya kenaikan harga dan nantinya dengan kenaikan harga plastik dapat menekan konsumsi plastik sehingga akan mencari alternatif produk pengganti plastik. Efektivitas cukai plastik dapat dinilai dari sejumlah indikator antara lain penurunan konsumsi plastik, peningkatan alternatif plastik yang ramah lingkungan, pendapatan negara melalui cukai plastik, penurunan volume limbah plastik, kesadaran perilaku masyarakat, serta tingkat investasi infrastruktur daur ulang.
Beberapa negara telah mengimplementasikan kebijakan cukai plastik dengan hasil yang baik. Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan dalam kajian ekstensifikasi barang kena cukai kemasan plastik dan wadah plastik (2020) memakai benchmark dalam beberapa negara, namun sudah ada beberapa negara yang memiliki hasil dalam penerimaan cukai plastik yaitu:
1. Estonia, tarif cukai kemasan plastik 2,5 euro/kg. Menurut Laspada (2022) yang mengkaji komposisi sampah di pinggir jalan Estonia tahun 2005 sebelumnya menyumbang 80% menjadi 10% dari sampah ditemukan sepanjang jalan. Selain itu dalam tingkat pengembalian wadah secara umum mencapai 82% dan 92% khusus botol PET (Schneider et al., 2021).
2. Latvia, negara ini mengenakan cukai plastik dengan jenis kemasan polystyrene dikenakan tarif lebih tinggi (1,56 Euro/Kg) dibanding jenis kemasan plastik lainnya (1,22 Euro/Kg). Dengan pendapatan cukai kantong plastik yang menurun sejak 2008 bahwa terjadi penurunan pendapatan cukai. Menurut pejabat MoE jumlah kantong plastik belanja digunakan menurun
cepat sejak diperkenalkannya cukai kantong plastik 2008.
3. Finlandia, mengenakan pungutan wadah minuman ringan dan beralkohol dengan skema tarif lebih rendah jika wadah dapat didaur ulang. Dampaknya menurut PALPA (2016), sehingga Finlandia secara konsisten mencapai pengembalian yang tinggi dalam sistem deposit wadah daur ulangnya dan mencapai peningkatan.
4. Denmark, mengenakan cukai atas plastik sesuai dengan bahan dengan tarif yang berbeda-beda. Sebagai negara pertama menerapkan kebijakan cukai atas penggunaan kantong plastik di tahun 1994, konsumsi kantong plastik mengalami reduksi hingga 50% dari angka 800 juta kantong menjadi 400 juta kantong (Matinho, 2017).
5. Belgia, pengenaan cukai plastik jenis polystyrene dan PVC sebesar 3,85 euro/kg. Kebijakan environmental taxes terbukti efektif di Belgia karena pencapaiannya mengurangi kantong plastik sekali pakai sebanyak 60% di tahun 2008 sampai 2009 (Nugraha, 2019), namun kebijakan ini kurang insentif untuk melakukan daur ulang.
Penerapan cukai plastik memiliki potensi pengurangan dampak negatif plastik dengan melihat dalam penerapan cukai plastik di beberapa negara yang berhasil dan efektif untuk mengurangi konsumsi plastik, mendorongan masyarakat menggunakan barang yang environmentally sustainable dan ramah lingkungan, dan mekanisme insentif untuk mendaur ulang hasil cukai plastik. Indonesia dapat belajar untuk menyeimbangkan tarif cukai plastik dengan insentif material daur ulang, memperkuat infrastruktur pengelolaan limbah, dan edukasi masyarakat.
Indonesia yang direncanakan akan mengenakan cukai plastik senilai Rp200/lembar atau Rp30.000/kg. Implementasi tarif ini dilakukan saat barang keluar dari pabrik untuk produksi dalam negeri atau pengimporan kantong plastik sehingga dikenakan terhadap produsen dan importir. DJBC berperan sebagai registrator pabrik dan importir, auditor, dan pelaporan produksi. Menurut Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan dalam kajian ekstensifikasi barang kena cukai kemasan plastik dan wadah plastik (2020) bahwa fasilitas cukai berpotensi menghasilkan tambahan penerimaan negara sebesar Rp3,3 Triliun. Menurut Febri Pangestu, analis Kebijakan Badan Kebijakan Fiskal sebagaimana dikutip oleh Ginting (2022), penerimaan negara cukai produk plastik dipergunakan dasar perhitungan alokasi anggaran kegiatan penanggulangan pencemaran atau kerusakan, pemulihan lingkungan, pengembangan industri daur ulang dan inovasi produk pengganti produk
plastik.
Penerapan cukai plastik di Indonesia sering dianggap sebagai langkah progresif untuk mengurangi dampak lingkungan. Namun, tidak sedikit pihak yang mempertanyakan apakah kebijakan ini benar-benar efektif atau hanya menjadi retorika simbolis tanpa dampak signifikan. Kebijakan ini masih perlu diuji berkenaan dengan ability to pay dan willingness to pay masyarakat. Kekhawatiran utama adalah bagaimana kebijakan ini akan diterapkan di tengah sistem pengelolaan limbah plastik yang belum optimal dan ketidakmerataan fasilitas daur ulang. Tanpa adanya pengawasan yang ketat, cukai plastik berpotensi hanya menjadi tambahan beban bagi konsumen tanpa mendorong perubahan signifikan dalam perilaku produsen atau masyarakat. Maka jika diterapkan tanpa kena mekanisme yang benar maka rencana pengenaan cukai plastik hanya menjadi langkah simbolis. Belajar dari beberapa negara yang kebijakannya tanpa adanya edukasi publik dan insentif daur ulang yang baik.
Anggapan bahwa cukai plastik lebih berorientasi pada penggalangan dana bagi pemerintah daripada menjadi upaya nyata untuk mengurangi polusi plastik. Pendapatan dari cukai plastik sering kali tidak disertai mekanisme alokasi yang jelas untuk mendukung program lingkungan, seperti pembangunan fasilitas daur ulang atau kampanye edukasi publik. Akibatnya, kebijakan ini bisa kehilangan legitimasi sebagai langkah yang benar-benar pro-lingkungan. Oleh sebab itu pemerintah perlu
menyeimbangkan aspek fiskal dan lingkungannya. Untuk memastikan efektivitasnya, pemerintah harus mengarahkan pendapatan cukai pada pengembangan infrastruktur daur ulang, mendorong penggunaan bahan alternatif yang berkelanjutan, dan menetapkan tarif berbasis risiko lingkungan. Dengan pendekatan ini, cukai plastik dapat berfungsi sebagai langkah nyata menuju keberlanjutan, bukan sekadar retorika simbolis.